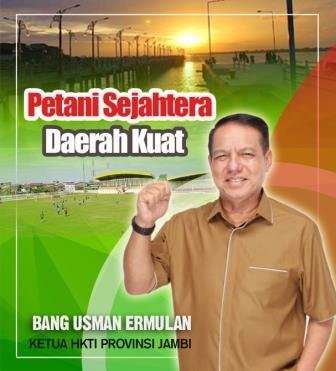Akhirnya, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Istana Negara. Kenaikan BBM diberlakukan sejak jam 14.30, Sabtu 3/9 atau satu jam setelah diumumkan pemerintah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif yang mendampingi Presiden Jokowi menjelaskan besarnya kenaikan BBM. Jenis pertalite dari harga Rp. 7.650 per liter naik menjadi Rp 10.000 per liter, solar dari Rp 5.150 per liter naik Rp 6.800 per liter, pertamax dari Rp 12.500 per liter naik Rp 14.500 per liter.
“Saat ini pemerintah harus membuat keputusan di tengah situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yang mengalihkan subsidi BBM,” kata Presiden Jokowi.
Alasan menaikkan harga BBM atau “menyesuaikan”, meminjam bahasa eufimisme pemerintah, karena naiknya minyak dunia pada level USD 99 per barel (saat ini US$ 85 per barel).
Menurut Menkeu Sri Mulyani diperkirakan subsidi dan kompensasi energi 2022 dari semula Rp 502,4 triliun berpotensi bertambah menjadi Rp 591 triliun. Bahkan ada Rp 100 triliun beban subsidi BBM tahun 2022 yang harus dibayarkan.
Dengan kata lain, APBN akan terlalu berat menanggung beban bila subsidi BBM tidak dikurangi. Terlebih lagi penggunaan subsidi BBM disebut-sebut pemerintah 70 persen dimanfaatkan oleh pemilik mobil, bukan masyarakat bawah atau miskin.
Berdasar kalkulasi atau hitungan ekonomi, keputusan pemerintah dapat diterima argumentasinya.
Pertanyaannya, apakah pemerintah tak ada cara lain lagi dalam menanggulangi beban APBN, selain menaikkan BBM ? Bukankah bila pemerintah menanggung beban subsidi BBM, itu juga berarti memihaki rakyat sendiri ?
Sebagaimana dikemukakan oleh Prof Din Syamsudin, mantan Ketua PP Muhammadiyah, meminta pemerintah tak menaikkan BBM. Caranya, pemerintah menunda proyek pembangunan IKN (Ibu Kota Negara), dan menunda pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung.
Betapa tidak. Dampak dari kenaikan BBM, tetap saja menyasar kelompok masyarakat miskin. Beban hidup rakyat semakin berat. Kemiskinan semakin terbuka. Lapangan kerja semakin sulit.
Lihat saja nanti. Pengusaha transportasi, pengusaha makanan minuman, angkutan umum, bahkan rumah sewa kos pun, dll, pastilah akan menaikkan dengan alasan naiknya biaya (cost) produksi atau operasional.
Meski kalangan miskin pada 31 Agustus telah digelontorkan Rp 24,7 triliun sebagai bantuan sosial tambahan, tidaklah dapat memenuhi kebutuhan. Sebelum BBM naik saja harga-harga kebutuhan pangan, seperti cabai, bawang, telur, sudah naik.
Inflasi pasti naik dan tak terhindar. Daya beli warga berkurang, dan harga-harga kebutuhan pokok menjadi mahal.
Kalangan buruh atau pekerja, meski mereka mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT), tetap saja akan menuntut kenaikan upah.
Kalangan pengusaha dari APINDO dipastikan akan ngotot untuk menolak kenaikan upah. Saling ngotot dan saling gugat pun tak terhindar antara buruh dan APINDO. Unjuk rasa pun tak terhindarkan.
Bantalan sosial, istilah pemerintah untuk memberi bantuan kepada rakyat miskin dan buruh, tidaklah cukup mengatasi kebutuhan dan beban rakyat miskin. Apalagi bantalannya hanya bersifat sementara.
Pengamat politik, Ujang Komarudin mengatakan, dampak kenaikan BBM mengurangi kepercayaan publik kepada Presiden Jokowi akan janji-janji politiknya.
Kata Ujang, meski pemerintah telah pintar dengan memberi BLT kepada warga miskin dan kalangan buruh, tetap saja kepercayaan kepada Jokowi tetap turun. Sebab, janji politik Jokowi pada Pilpres lalu yang akan menstabilkan harga dan membuka lapangan kerja belum terpenuhi (WartakotaLivecom, 3/9/2022).
Kenaikan BBM di tengah situasi sulit saat ini, tidaklah mengenakkan bagi siapa saja. Bukan kalangan miskin saja dibuat susah, kalangan menengah atas pun merasa kesulitan.
Pentingkah kepercayaan publik dipertahankan di tengah beban hidup masyarakat yang semakin sulit, sepertinya tak perlu. Sebab, naik turunnya kepercayaan publik, cukup diserahkan kepada lembaga survey.
Itulah BBM, beban berat masyarakat.
*Ketua Dewan Pakar JMSI Kepri