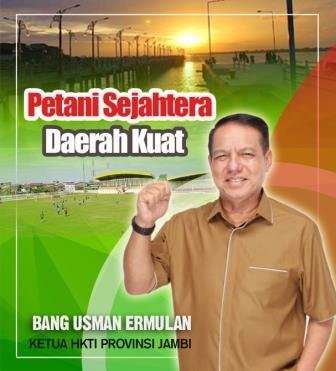Setelah Mahkamah Konstitusi mencabut pasal larangan keluarga petahana mencalonkan diri dalam Pilkada, semakin menyuburkan praktik dinasti politik di Indonesia. Sejatinya, pemilihan kepala daerah 2020 masih berlangsung sekitar 4 bulan lagi yaitu, pada 9 Desember 2020 bertepatan dengan hari Antikorupsi Internasional.
Pilkada serentak untuk 270 daerah tersebut sudah ditunda dari sebelumnya yang dijadwalkan pada 23 September 2020, namun akibat pandemi Covid-19 KPU pun merevisi pesta demokrasi lima tahunan di daerah tersebut. Rincian daerah yang akan melakukan pesta politik adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota dan karena memang waktunya sudah sempit, sejumlah nama sudah mulai memunculkan diri sebagai calon kepala daerah dengan mengantongi dukungan dari partai politik.
Persoalannya, nama-nama yang muncul adalah kerabat dari tokoh-tokoh politik nasional dan daerah, bahkan sebagian berusia muda dan tidak punya rekam jejak di dunia politik sebelumnya. Kerabat tokoh politik nasional yang sudah mengantongi dukungan dari partai politik misalnya Gibran Rakabuming Raka (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/PDI-P), putra Presiden Joko Widodo, sebagai bakal calon wali kota Solo; Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (Gerindra), sebagai bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan Siti Nur Azizah (Demokrat), putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, sebagai bakal calon wali kota Tangsel.
Selanjutnya Bobby Nasution (Partai Gerindra), menantu Presiden Joko Widodo yang akan maju sebagai calon Wali Kota Medan; Hanindhito Himawan Pramana (PDI-P), putra Sekretaris Kabinet Pramono Anung, sebagai bakal calon bupati Kediri; Irman Yasin Limpo (Partai Golkar), adik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, sebagai bakal calon wali kota Makassar; dan Titik Masudah (Partai Kebangkitan Bangsa) yang merupakan adik Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menjadi bakal calon wakil bupati Mojokerto.
Politik di Jambi, ada Yunninta Asmara (Partai Golkar) istri Bupati Batanghari Syahirsah. Yunninta menjabat Wakil Ketua DPRD Batanghari mencalonkan diri sebagai bupati, menggantikan suaminya. Kemudian, putra pasangan almarhum Abdul Fattah (PAN) dan Almarhumah Sofia Joesoef, Wakil Bupati Batanghari periode 2016-2021, Hafis Fattah memilih berpasangan dengan Camelia Hasip (Demokrat) anak dari mantan wakil Gubernur Jambi, H. Hasip Kamaluddin Syam. Disana, istri Hafiz, Anita Yasmin merupakan Ketua DPRD.
Selain Pemilihan Gubernur Jambi dan di Batanghari, daerah lainnya melangsungkan pemilihan yakni Kota Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Bungo. Di Kota Sungai Penuh, Fikar Azami (Demokrat) mantan Ketua DPRD di daerah itu, ikut menggantikan ayahnya, Asafri Jaya Bakri. Asafri melaju sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur Jambi mendampingi Walikota Jambi, Syarif Fasha. Pasangan ini baru didukung dua partai, NasDem dua kursi dan PPP tiga kursi.
Di Tanjung Jabung Barat, pertarungan antar keluarga merebut kekuasaan antara Cici Halimah – Istri Bupati Safrial—maju mengantikan suaminya. Dan, Mulyani Siregar, adik kandung Safrial kini sebagai Ketua DPRD di daerah itu. Cici dan Mulyani sama-sama kader PDI Perjuangan.
Tak mau ketinggalan, Safrial justru melaju sebagai Bakal Wakil Gubernur Jambi mendampingi petahana, Fachrori Umar. Pasangan ini baru saja mengantongi rekomendasi Gerindra tujuh kursi dan Hanura dua kursi. Di Bungo, nama menantu mantan Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus, Mezi Arsento dan Riduwan Ibrahim ipar Gubernur Jambi sekarang, sempat menegaskan maju sebagai nomor satu. Seiring berjalan keduanya mengurungkan niatnya.
Total kursi di DPRD Provinsi Jambi 2019-2024 sebanyak 55 kursi, syarat mutlak gabungan partai politik minimal didukung 11 kursi. Pengamat Politik dari Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan (Pusakademia), Mochammad Farisi menyebutkan, bahwa Pilgub Jambi bisa saja menjadi empat pasang, jika peluang Cek Endra (Bupati Sarolangun) bersama Ratu Munawaroh mendapat PDI Perjuangan pemilik sembilan kursi, untuk melengkapi dukungan sebelumnya yakni Golkar tujuh kursi.
“Demokrat ke Fasha dan PAN ke Fachrori. Itu kalau Al Haris mau melepaskan PAN. Jika tidak, Demokrat penentu Pak Fasha dan Pak Fachrori. Harus ada yang tersingkir,” kata Farisi.
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril mengatakan munculnya politik dinasti dalam pemerintahan sangat rentan disalahgunakan dan cenderung melahirkan korupsi. Ia mencontohkan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Klaten Sri Hartini.
“Klaten, ada banyak sekali dugaannya. Contoh paling sempurna bagaimana politik dinasti bekerja,” kata Oce di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW),” kata dia beberapa waktu lalu.
Oce menilai politik dinasti di Klaten dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi keluarga. Misalnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diduga koruptif. Ia menyebut korupsinya dilakukan terstruktur dan masif seperti proyek pengadaan dan perizinan.
Koordinator ICW Donal Fariz mengatakan ada dua faktor yang memicu korupsi oleh politik dinasti. Pertama, adalah motivasi untuk menguasai aset di daerah. Kekuasaan itu bakal disalurkan dalam bentuk korupsi penguasaan barang jasa, alih fungsi hutan, dan tambang. “Menjadi akses dan jembatan untuk masuk ke sumber daya ekonomi.”
Selain itu, kata Donal, faktor biaya politik yang tinggi. Membangun politik dinasti membutuhkan uang yang besar. Menurut Donal untuk menjadi wali kota, biaya politik yang dikeluarkan mencapai Rp20 miliar. Bahkan untuk menjadi gubernur di DKI Jakarta bisa mencapai Rp100 miliar.
Sehingga, apabila seseorang telah terpilih menjadi kepala daerah maka mereka memperhitungkan biaya yang harus dikeluarkan untuk menghidupi organisasi masyarakat, kepemudaan, hingga adat. Hal itu memicu kepala daerah mencari sumber dana hingga mengakibatkan perilaku koruptif.
Menurut Donal, politik dinasti tak hanya tampak di Klaten. Namun juga di Banten. Ia menilai dinasti pemerintahan di Banten tercipta dengan lebih dahulu membentuk dinasti politik. Sehingga politik dinasti di pemerintahan merupakan cerminan dari dinasti politik yang terbentuk.
Politik dinasti
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha mengatakan politik dinasti atau politik kekerabatan (kinship politics) adalah fenomena yang sudah lama terjadi yaitu ketika penguasa mendasarkan legitimasi kekuasaannya melalui jalur keturunan dengan mengapitalisasi pertalian darah, kekayaan, spiritual hingga keahlian politik.
Penyebab pertama munculnya dinasti politik adalah nilai-nilai feodalisme masih kuat di Indonesia karena ada sisa psikologis nilai kerajaan/kesultanan hingga berujung pada personalisasi tokoh dan pada titik tertentu dinasti politik terbangun sejak lama.
Egi mencontohkan Soekarno yang dilanjutkan Megawati lalu Puan Maharani, kemudian Soeharto dilanjut Tutut, Tommy, Titiek Soeharto. Namun sebagai catatan, kemunculan Megawati atau anak-anak Soeharto tidak bersifat instan.
Egi menjelaskan bahwa Megawati perlu menghadapi rezim untuk muncul ke tataran politik hingga akhirnya berkuasa, selanjutnya anak-anak Soeharto menjadi anggota Partai Golkar setelah Soeharto berkuasa sekian lama.
Faktor kedua penyebab dinasti politik adalah demokrasi elektoral dengan sistem pemilu langsung menyandarkan pada popularitas dan politik uang. Demokrasi elektoral dinilai membuka luas kesempatan setiap orang untuk mencalonkan diri namun yang diuntungkan adalah mereka yang sedang atau pernah berkuasa, populer, menguasai kekayaan atau punya basis dukungan yang kuat.
Artinya, desentralisasi dan demokrasi elektoral mempermudah kemunculan elit baru beserta keluarganya dalam politik, baik di level nasional maupun lokal. Faktor ketiga adalah pembiaran dari elit politik dan representasi formal serta faktor keempat tidak ada gerakan sosial terutama kelas menengah ke bawah yang kuat untuk menolak politik dinasti.
Menurut Egi, dinasti politik ini dapat menimbulkan sejumlah masalah, yaitu, pertama, nafsu untuk melanggengkan diri tidak bisa dikendalikan sehingga dapat menciptakan korupsi hingga pelanggaran HAM.
Masalah kedua, munculnya orang-orang dalam dinasti politik bukan ingin menjadikan politik sebagai upaya untuk mencapai kebaikan bersama (common good) tapi bertujuan untuk kepentingan pribadi, baik dirinya sendiri maupun keluarganya.
Masalah ketiga adalah tidak menekankan dari kemampuan atau kapasitas individu melainkan pada garis kekerabatan sehingga merusak sistem meritokrasi.
Masalah terakhir adalah merusak kesetaraan kesempatan bagi orang-orang yang tidak punya hubungan kekberapatan meski punya pengalaman dan kualitas sebagai pemimpin.
“Masalah dinasti politik ini tidak dapat dilihat dari kerangka demokrasi prosedural semata. Memang Indonesia punya kelengkapan alat demokrasi seperti parpol, pemilu, lembaga negara tapi dari kerangka substansial nilai dari demorkasi rusak karena tidak ada etika publik dan kesempatan warga berdemokrasi pun menjadi semu,” ungkap Egi.
Sedangkan Wakil Direktur Pusat Kajian Riset dan Politik (Puskapol) Universitas Indonesia Hurriah mengatakan dinasti politik di Indonesia dapat disebut sebagai neo-patrimonial karena proses regenerasi kekuasaan bukan ditunjuk langsung seperti rezim sebelumnya tapi melalui demokrasi prosedural.
Dinasti politik tersebut terjadi di Indonesia karena parpol menjadi bentuk monarki baru di Indonesia karena dimiliki satu orang tokoh yang kekuasaan turun menurun, seperti di PDIP dan Partai Demokrat bahkan meluas lewat jalur pemilu dan pilkada sehingga melanggengkan kekuasaan dan kekayaan.
Politik kekerabatan pun dapat bertahan karena memiliki akses politik dan pendanaan yang kuat. “Akses politik karena sebagian besar adalah petahana yang tengah menjabat atau menjadi pemimpin partai di daerah ditambah kepemimpinan politik di tingkat nasional memberikan kemudahan akses pencalonan,” kata Peneliti CSIS Arya Fernandes.
Parpol yang bukan “dimiliki” keluarga juga dengan senang hati memilih orang yang punya hubungan kekerabatan dengan penguasa tertentu karena waktu pemilihan legislatif yang berjarak dengan pilkada serta faktor personal caleg dalam pileg.
Arya menilai jarak waktu yang panjang antara pileg dan pilkada tidak memberikan insentif ke partai untuk mendukung ke calon tertentu sejak awal sehingga partai akan “langsung” memilih orang-orang yang sudah punya modal kedekatan, popularitas hingga pendanaan yang kuat.
“Ada calon pemimpin daerah yang sudah pernah korupsi, masuk penjara tetap menang pilkada, tidak ada risiko yang dilihat parpol saat mencalonkan calon yang tidak punya kapasitas. Partai kecil pun pragmatis memberikan dukungan ke partai besar bila dijanjikan akses ke APBD atau regulasi dan kesulitan mendorong orang-orang yang bagus,” tambah Arya.
Langkah selanjutnya
Untuk menyelesaikan masalah oligarki politik dinasti menurut Egi tidak bisa menggantungkan semata pada perbaikan undang-undang parpol atau pemilu.
“Perbaikan parpol membutuhkan perubahan regulasi, regulasi ada di DPR dan DPR terdiri dari parpol-parpol sehingga representasi formal sudah membusuk. Representasi formal ini juga sulit diubah karena dijaga aparatusnya baik ‘ideology regime apparaturs’ seperti ‘buzzer’ di medsos maupun ‘repressive regime apparatus’ misalnya kepolisian,” ungkap Egi.
Tawaran untuk membuat upaya tandingan (counter) terhadap representasi formal yang membusuk yang dilakukan secara kolaboratif antara “civil society organization”, media, akademisi hingga komunitas-komunitas di masyarakat.
Tujuan upaya tandingan itu adalah agar parpol tidak mencalonkan calon-calon pemimpin yang tidak punya kapasitas sejak awal dan masyarakat juga tidak perlu memilih orang-orang yang tidak kredibel atau bahkan hanya mementingkan keluarganya sendiri. (Berbagai sumber)