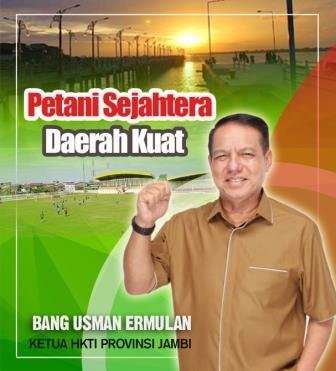Oleh Nurul Fahmy
Taklid (taqlid) buta yang berkembang soal jurnalisme adalah wartawan tidak boleh beropini. Pandangan ini jelas telah ditafsir secara salah. Kemudian digunakan untuk menjegal kebebasan individu (jurnalis) dalam menyatakan pendapatnya (opini) terhadap sesuatu hal.
Gejala ini, gejala pelarangan wartawan untuk berpendapat ini, lucunya, biasanya, lebih bersifat politis. Maksudnya, jurnalis diharamkan berpendapat soal pilkada, pilpres dan pilkades atau lain-lain pemilihan.
Kalau sikit saja wartawan berpendapat–soal politik–, maka sinisme sudah muncul, bahkan makin meluas; dituding ikut-ikutan berpolitik praktis.
Alih alih meluruskan paham yang salah ini, mereka, para wartawan itu, celakanya, justru bertaklid buta juga dengan pandangan wartawan tidak boleh beropini itu. Alhasil, banyak kali kita lihat wartawan seperti apatis, a-historis dan acuh tak acuh dengan kondisi politik, sejarah dan termasuk kejadian atau ketidakadilan yang terjadi hari ini.
Sebagaimana taklid, orang yang meyakini paham ini biasanya tidak begitu mengerti bagaimana jurnalis bekerja, dan seperti apa struktur kerja mereka. Mereka beranggapan, kerja wartawan itu tunggal, bersifat pribadi dan sehingga bisa saja sentimentil. Tentu tidak sesederhana itu, Ferguso!
Kerja wartawan itu kolektif. Sebuah laporan yang final, dalam jajaran redaksi yang ideal, merupakan buah kerja banyak orang. Meski perannya maksimal, namun laporan reporter hanya dapat terbit berdasarkan persetujuan banyak pihak diatasnya, setelah melalui proses penyuntingan oleh redaktur. Dengan demikian, di media yang tertib, sang wartawan tentu saja tidak bisa menyelipkan pandangan pribadinya dalam sebuah berita.
Lantas, apakah wartawan boleh beropini? Tidak. Tentu saja tidak boleh, kalau beropini di dalam berita. Wartawan hanya boleh beropini di luar berita, seperti di kolom opini, media sosial ataupun blog pribadi. Tapi bukan berarti media tidak dapat menyampaikan opini redaksi dalam beritanya. (Soal bagaimana opini pribadi bisa masuk di dalam berita akan saya tulis di bagian kedua tulisan ini).
Menuliskan opini adalah cara mengembangkan gagasan dan mengemukakan pandangan. Dia juga berguna untuk menajamkan pikiran, menghindarkan diri dari gejala pikun dan pelupa. Cara lain untuk berargumen secara benar dan bertanggung jawab. Dan beropini tentu saja merupakan hak sipil dalam negara demokrasi, yakni bebas berbicara dalam rangka mengembangkan pendapat umum.
Mengembangkan pendapat umum ini juga merupakan peran dan tanggung jawab pers, sebagai pilar ke empat demokrasi. Pers dapat memuat pendapat atau opini pengamat (ahli) di dalam beritanya. Berita jenis ini, biasanya bukan jenis berita ringan (straight news). Tapi umumnya berita yang bertujuan kritis. Untuk mengubah cara pandang publik, mempengaruhi kebijakan pemerintah dan merupakan sikap redaksi terhadap suatu peristiwa.
Di bagian ini, sedikit yang menyadari bahwa ‘opini redaksi’ berperan banyak dalam isi berita. Tapi jelas bukan opini individu. Ini adalah pandangan redaksi yang menggunakan pengamat atau ahli yang sejalan dengan media yang bersangkutan.
Meski dalam beberapa kasus, kebijakan redaksi, keberpihakan mereka, biasanya lebih mewakili afiliasi bisnis dan politik si pemilik media. Kalau idealnya, sih, kebepihakan media itu hanya pada kebenaran dan kepada rakyat. Tapi faktanya dapat kita simak sendiri.
Metro TV dan Berita Satu, misalnya, bisa jadi hanya akan meminta pendapat para ahli yang sejalan dengan keinginan mereka ketika membahas soal rezim Jokowi. Begitu pula TVOne, RMOL atau Tirto.id akan menulis dengan sudut pandang para ahli yang sesuai dengan kebijakan redaksi mereka.
Di bagian lain, opini redaksi biasanya ditulis khusus oleh pemimpin redaksi dan dimuat di kolom khusus yang bernama tajuk rencana. Namun sekali lagi ini adalah pandangan umum redaksi. Bukan pandangan individu. Meski dibanyak kasus juga, kebijakan redaksi merupakan pandangan umum pemimpinnya.
Kemudian, jika wartawan tidak dapat mengembangkan pendapat pribadi secara langsung, dimana dia bisa bebas bersuara?
Wartawan boleh saja menulis apa saja, termasuk soal politik sekalipun. Ketika menuliskan opininya, wartawan tidak dapat dikait-kaitkan dengan profesinya. Apa yang dituliskannya adalah tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab redaksi. Opini bukan laporan jurnalistik.
Di pengujung masa Orde Baru yang megah, wartawan Seno Gumira Ajidarma (kini Rektor IKJ) mengatakan, “Ketika Jurnalisme Dibungkam, Sastra Harus Bicara”. Jurnalisme, tulis dia, terikat oleh seribu satu kendala, dari bisnis sampai politik untuk menghadirkan dirinya. Buku Sastra bisa dibredel, tetapi kebenaran dan kesustraan menyatu bersama udara, tak tergugat dan tak tertahankan.
Namun di zaman kiwari, seandainya jurnalisme telah kehilangan marwahnya, dan sastra hanya dipenuhi “penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan, sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya”–mengutip Rendra dalam Sajak Sebatang Lisong—maka opinilah yang harus bekerja.
(Penulis adalah Jurnalis, Ketua IWO Provinsi Jambi)