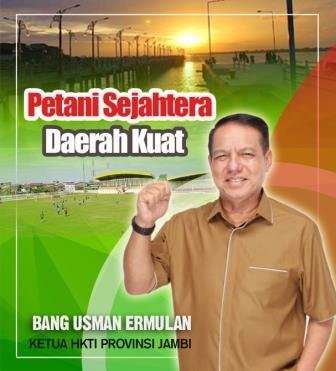Oleh: Bahren Nurdin (Pengamat Sosial dan Kebijakan Publik – Tinggal di Australia)
Dalam beberapa tahun terakhir, kita semakin sering mendengar berita mengejutkan tentang mahasiswa yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Fenomena ini tentunya bukan hanya tragedi personal, tetapi juga cerminan krisis sistemik dalam dunia pendidikan tinggi kita.
Agaknya saya merasa perlu untuk menyoroti isu krusial ini dan mengajak kita semua untuk peduli juga memberi perhatian serius.
Dunia kampus, yang seharusnya menjadi tempat pengembangan diri dan intelektual, kini berubah menjadi arena pertarungan mental bagi banyak mahasiswa. Beban akademik yang mencekik, dengan jadwal kuliah padat dan tumpukan tugas yang seolah tak berujung, boleh jadi menjadi salah satu pemicu utama stres. Belum lagi ekspektasi untuk selalu mendapat nilai tinggi, yang kerap kali datang dari diri sendiri, keluarga, atau bahkan institusi.
Kompetisi yang semakin ketat di era globalisasi turut memperparah situasi. Mahasiswa merasa terpaksa bersaing secara tidak sehat demi mendapatkan beasiswa atau peluang karir yang terbatas. Sikap perfeksionis yang berlebihan semakin memperburuk keadaan, menciptakan rasa takut gagal yang melumpuhkan.
Ironinya, di tengah keramaian kampus, banyak mahasiswa justru mengalami isolasi sosial. Waktu yang tersita untuk memenuhi tuntutan akademik membuat mereka kehilangan momen berharga untuk membangun koneksi sosial dan dukungan emosional dari teman sebaya. Situasi ini diperparah oleh ketidaksiapan sebagian mahasiswa dalam beradaptasi dengan lingkungan baru dan mengelola waktu secara efektif.
Faktor ekonomi juga tidak bisa diabaikan. Biaya pendidikan yang terus melonjak menjadi beban tersendiri. Tidak sedikit pula mahasiswa yang terpaksa mencari pekerjaan paruh waktu demi membantu orang tua atau untuk bertahan hidup. Hal ini semakin menambah tekanan pada persoalan akademik yang mereka hadapi.
Lebih memprihatinkan, banyak institusi pendidikan tinggi belum memiliki sistem dukungan yang memadai. Layanan konseling sering kali terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Program kesehatan mental masih dianggap sebagai ‘kemewahan’ daripada kebutuhan mendasar.
Lantas, apa yang mungkin dapat dilakukan?
Pertama, perlu ada reformasi kurikulum yang menekankan keseimbangan antara pencapaian akademik dan kesejahteraan mental. Institusi pendidikan harus mulai mempertimbangkan beban akademik yang lebih manusiawi.
Kedua, peningkatan layanan dukungan mental di kampus adalah suatu keharusan. Konseling harus tersedia dan mudah diakses. Stigma seputar kesehatan mental harus dihapuskan melalui edukasi yang berkelanjutan. Terpenting, bimbingan spiritual dan penguatan keimanan wajib dilakukan tiada henti.
Ketiga, perlu ada pelatihan keterampilan hidup (soft-skill) bagi mahasiswa, termasuk manajemen stres, pengelolaan waktu, dan resiliensi emosional. Ini akan membantu mereka menghadapi tekanan dengan lebih baik.
Keempat, institusi pendidikan harus aktif membangun komunitas yang suportif. Program mentoring, kelompok dukungan sebaya, dan kegiatan sosial yang bermakna dapat membantu mengurangi isolasi.
Terakhir, kita perlu meninjau ulang definisi kesuksesan dalam pendidikan tinggi. Fokus tidak boleh semata-mata pada nilai akademik, tetapi juga pada pengembangan diri yang holistik.
Saya ingin menekankan, harus ada kesadaran kolektif bahwa masa depan bangsa ini bergantung pada kesehatan fisik dan mental generasi mudanya. Para pengambil kebijakan sudah saatnya bertindak untuk menciptakan lingkungan akademik yang tidak hanya mendorong keunggulan intelektual, tetapi juga memupuk kesejahteraan mental.
Jika kita tidak peduli, kita berisiko kehilangan lebih banyak talenta muda yang berharga. Mari bersama-sama menciptakan perubahan demi masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa. Semoga.